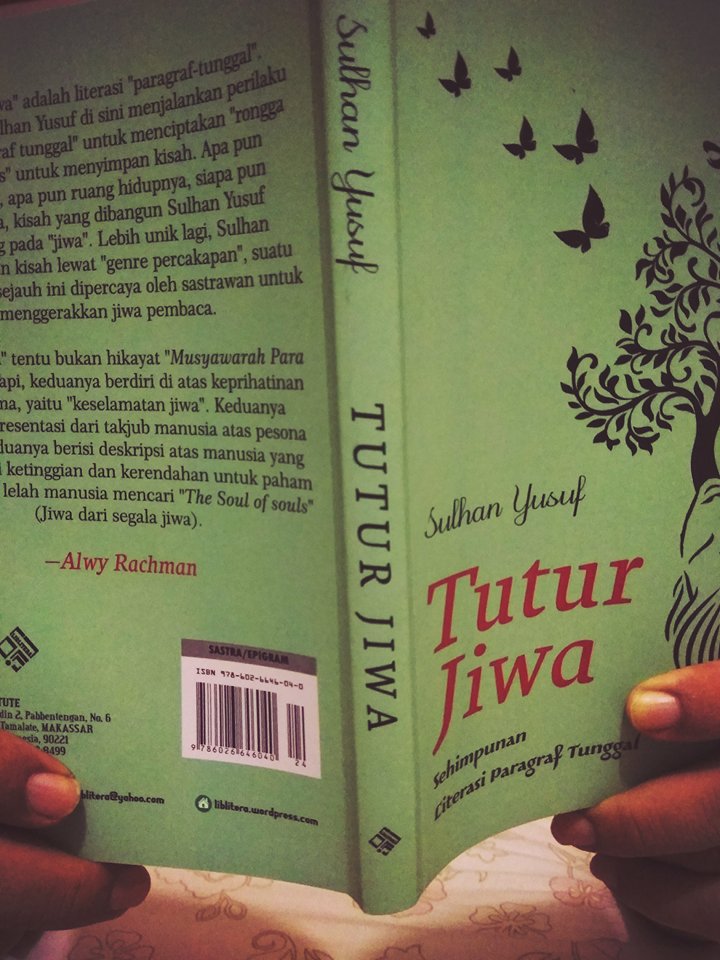Fore play, pengantar dini untuk hanyut dalam kenikmatan selanjutnya. Sengaja dipilih fore play dibanding warming up dalam mengawali “membaca” karya bernas Tutur Jiwa Sulhan Yusuf. Pada warming up mengandung makna pendahuluan mengantar kepada fokus dan menguras energi, sementara itu fore play juga pendahuluan, namun lebih pada makna kesantaian dan kenikmatan serta mengakumulasi energi. Dengan fore play ini, diharapkan pembaca dapat larut menikmati legitnya kedalaman rasa dan makna saat membaca Tutur Jiwa, berharap mencapai klimaks pemahaman dalam setiap paragrafnya.
Salah satu kunci memahami setiap paragraf tunggal Tutur Jiwa Sulhan Yusuf adalah menyelami relasi antara Han dan Sang Guru. Sang Guru dengan santun dan lembut namun penuh ketegasan makna senantiasa membimbing Han ke kedalaman makna lautan kebijaksanaan. Han diantarkan memasuki wilayah keluasan dan kedalaman makna setiap peristiwa yang dialami dengan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya.
Dengan keberadaan masing-masing, secara jeli dapat dilihat relasi keduanya berupa: Han mewakili “aku individual(=aku)” dan Sang Guru mereprentasikan “Aku Universal(=Aku)”. Sangat tampak dalam percakapan keduanya, Sang Guru selalu dan senantiasa membimbing Han ke keuniversalan makna setiap peristiwa yang dibincang. Misal Sang Guru bertitah: “Han…, Ramadan sebagai nama bulan boleh pergi meninggalkanmu, tetapi sebagai jalan kesucian tetaplah abadi buat sulukmu”(hal. 185). Di sini, Ramadan dimaknai bukan sekadar bulan suci yang berisikan 30 hari, akan tetapi telah bertambah makna menjadi tarekat yang tak berbatas hari. Perluasan dan pendalaman makna semacam ini ditemukan dalam setiap tutur Sang Guru, secara halus tak terasa, kepada Han, seolah dengan kelihaian penuh, menenggelamkan Han ke dalam kenikmatan lautan makna dan kebijaksanaan yang begitu tinggi. Hal ini adalah efek dari Sang Guru berdimensi “Aku Universal”.
Ada tiga hal yang patut dicermati sebagai fore play untuk menikmati setiap menu sajian Tutur Jiwa yaitu, pertama, dari mana sumber tutur bijak Sang Guru berasal? Kedua, mengapa Sang Guru senantiasa bertutur bijak? Ketiga, mengapa Han mengikut saja, bahkan menikmati tutur bijak Sang Guru? Tidakkah perlu sesekali Sang Guru keseleo lidah dalam bertutur atau tetiba Han menggurui Sang Guru? Kesemua tanya tersebut jawabannya bisa didapat dari hasil menelisik hubungan mistis antara Han dengan Sang Guru.
Relasi Han dengan Sang Guru dapat diurai dengan fenomenologi. Han sebagai “aku fenomena” dan Sang Guru sebagai “Aku noumena”. “aku fenomena” bergelut dengan dunia nyata, sementara “Aku noumena” bersemayam di alam imanen. Menurut Kant, noumena tak tersentuh, kita hanya dapat membaca fenomena saja. Menurut mazhab ini, pengetahuan itu hasil dari pergumulan empirik, artinya yang dapat memiliki pengetahuan itu adalah fenomena, karena fenomenalah yang menyentuh dunia empirik, bukan noumena. Bila konsisten dengan cara pandang ini, semestinya Han-lah sebagai “aku fenomena” yang mengajar Sang Guru yang “Aku noumena” sebab ranah pengetahuan adalah ranahnya fenomena, ranahnya Han, bersemayam dalam realitas nyata. Kenyataannya terbalik, dalam Tutur Jiwa Sang Guru yang “Aku noumena” yang bertitah pada Han yang “aku fenomena”, padahal tempat bersemayamnya Sang Guru di alam noumena, bukan tempat bertumbuh-kembangnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, selain ada dua aku yang eksis yang memungkinkan Han membantah Sang Guru karena kesetaraan wujud, pendekatan ini tidak mampu menjawab tuntas ketiga pertanyaan di atas, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lain.
Dengan cara lain, Relasi Han dengan Sang Guru dapat ditilik dari segi relasi ketunggalan wujud, pendekatan teori Wahdatul Wujud. Salah satu cara untuk menjelaskan teori ketunggalan wujud ini adalah dengan menganalisa kopula sebab-akibat. Analisa kopula ini dapat mengantarkan pada pahaman hakiki apakah wujud itu sebenarnya jamak atau tunggal. Dari peta wujud inilah nanti dapat dilacak di mana posisi Han dan Sang Guru beserta kualitas-kualitas masing-masing, termasuk setiap tutur mereka.
Secara umum dipahami bahwa pada kopula sebab-akibat terdapat tiga hal, yaitu sebab, akibat dan relasi keduanya. Pahaman ini, dengan sepintas, mengisyaratkan adanya tiga wujud, yaitu wujud sebab, wujud akibat dan wujud relasi keduanya. Namun jika dicermati lebih teliti, dari ketiganya, hanya sebablah yang memiliki wujud hakiki, akibat dan relasi sekedar penampakan luar dari wujud sebab. Wujud pada akibat dan relasi keduanya sebenarnya tidak ada, sebab keduanya bergantung wujud pada wujud sebab, sehingga yang memiliki wujud itu sesungguhnya hanyalah sebab. Oleh karena itu, secara wujudiah, akibat dan relasi sebab-akibat bergantung murni pada wujudnya sebab. Sehingga yang ada hanya wujud tunggal, selainnya adalah manifestasi, pancaran dari wujud tunggal tersebut.
Dalam konteks pemahaman di atas, mau atau tidak, Han dan Sang Guru harus dipandang sebagai wujud tunggal, bukan dua wujud secara individual berdiri sendiri. Yang membedakannya adalah siapa yang bergantung murni pada siapa atau perbedaan itu pada tingkat wujudiah yang mereka duduki dalam cakupan wujud tunggal.
Secara cerdik, Sulhan Yusuf yang tunggal membelah diri dalam buku Tutur Jiwa menjadi Han dan Sang Guru. Seolah hal ini menampakkan rentang wujud atau hirarki wujud yang ada dalam diri Sulhan Yusuf. Katakanlah, Han mewakili tingkat kerendahan wujud tertentu dan Sang Guru merepresentasikan ketinggian wujud tertentu pula, yang keduanya ada dalam diri Sulhan Yusuf. Tutur yang terjadi adalah, jika Han yang berkata kepada Sang Guru, maka kerendahan wujud bertutur kepada ketinggian wujud, sedangkan jika Sang Guru yang bertutur kepada Han, maka ketinggian wujud yang bertitah pada kerendahan wujud. Namun yang perlu dicatat adalah keduanya dalam wujud yang tunggal. Tutur keduanya adalah tutur yang menginternal, bukan mengeksternal, sehingga tidak membuka peluang untuk melahirkan wujud baru.
Untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas, Sang Guru sebagai “Aku Universal” pada ketinggian wujud tentu termuat dalam dirinya ketinggian pengetahuan pula, yang terekspresikan menjadi tutur-tutur jiwa kepada Han. Pengetahuan bijak ini bukan hasil dari pergumulan empirik sebagaimana yang terjadi pada alam fenomena, akan tetapi ia telah bersemayam sejak azali pada ketinggian wujud tersebut sebagai titisan dari pengetahuan bijak-Nya. Sehingga, setiap kali Sang Guru bertutur, tak lain yang terekspresikan adalah pengetahuan bijak setinggi makam wujudiah tempat bersemayam Sang Guru.
Ada pun Han, menduduki makam wujudiah dari kerendahan, akan ikut begitu saja pada titah Sang Guru, karena memang ketundukan wujudiah, mencucup segenap curahan pengetahuan bijaknya. Justru dengan manut semacam itu, Han mendapat keuntungan besar, yaitu pengetahuan bijak yang ia peroleh menjadi pendongkrak baginya untuk naik ke makam wujud yang lebih tinggi. Adalah logis jika telah mencucup pengetahuan bijak selama sekitar tiga tahun, Sang Guru mentasbihkan Han menjadi Guru Han, bukan sekedar akumulasi tutur bijak yang ia terima, akan tetapi seiring dengan itu terjadi peningkatan makam wujudiah. Mungkin sebelumnya Han menghuni di kerendahan makam wujudiah, namun kini berubah, Guru Han juga mendiami ketinggian makam wujudiah juga (hal. 209).
Dengan paradigma di atas, paragraf mana pun yang dibuka dalam Tutur Jiwa senantiasa akan ditemukan bahwa Sang Guru senantiasa bertitah dari ketinggian wujud memancarkan makamnya berupa tutur-tutur bijak yang jika direnungkan lebih dalam, akan meningkatkan makam wujudiah pendengarnya pula. Betapa indahnya Sang Guru bertutur: “Han…, karena tampangmu tidak begitu menawan, maka perbanyaklah tersenyum. Moga rupawan wajahmu akibat senyum, terpampang merona selebar permadani yang memukau semesta,” (hal. 177). Bayangkan, kekurangberuntungan di wajah, melaui tutur bijak Sang Guru, berubah menjadi tebar pesona dengan percaya diri tinggi.
Pada akhirnya, setiap paragraf Tutur Jiwa merupakan untaian mutiara kearifan ilahi yang ditutur dari ketinggian makam wujudiah yang diungkap di kekinian dan kedisinian sehingga memungkinkan para pembaca menikmati setiap sajiannya untuk menyelam ke dasar palung kebijaksanaan yang sesungguhnya merupakan pancaran dari Dia Yang Mahabijak. Sebagaimana karya-karya lain yang ditulis pada ketinggian makam kebijaksanaan mengabadi, maka Tutur Jiwa pun akan mengabadi, bertutur kepada siapa pun tiada henti menularkan virus kebijaksanaan pada kehidupan.