Prolog
Di era cyberspace (dunia maya), kebutuhan akan informasi sangat mudah terpenuhi. Dengan dimediasi oleh teknologi informasi, masyarakat semakin mudah mengakses peristiwa-peristiwa terkini baik berupa foto, video, maupun teks yang berseliweran di media massa dan media sosial. Cyberspace juga kini menjadi realitas dan ruang pengalaman baru manusia di era masyarakat informasi. Pun, di dunia maya, semua orang bisa menyebarkan informasi kapan saja karena mediumnya disediakan dengan varian yang melimpah. Anda bisa beropini di Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Blog dst.
Saat penyebaran dan konsumsi informasi semakin mudah di era cyberspace, mengapa kebenaran justru semakin sulit ditemukan? Perdebatan apakah Covid-19 itu nyata atau tidak, konspirasi atau memang memang fakta biologis yang muncul tanpa kita duga justru terjadi di era teknologi informasi yang serba memudahkan. Kita tahu bahwa saat ini masyarakat terbelah antara percaya dan tidak percaya dengan Covid-19. Keyakinan yang terbelah tersebut dikarenakan sulitnya menyaring informasi yang pasti di dunia cyberspace.
Jika teknologi informasi menjadi jembatan antara masyarakat dan realitas, seharusnya kebenaran semakin mudah disingkap mengingat persepsi manusia terhadap realitas semakin luas. Anda bisa kemana saja dengan membawa smartphone sambil mencari informasi terkini melalui Google. Semua orang bahkan bisa menambah pengetahuannya tentang kondisi sosial dan politik di Eropa tanpa harus menginjakkan kaki di sana. Dan semua itu bisa dilakukan dengan dimediasi oleh teknologi informasi. Dahulu kala, melihat detail-detail bulan sangat sulit dilakukan. Tapi kini, video dan foto astronomi bisa diakses dengan mudah di dunia maya. Kita tak perlu ke bulan hanya untuk menyaksikan kemegahan ciptaan Tuhan tersebut.
Jadi perkembangan teknologi sejatinya turut mengubah cara manusia berpengetahuan. Maka seharusnya kebenaran dan fakta-fakta bisa semakin mudah ditemukan dengan mediasi teknologi. Ketika Antonie Van Leeuwenhoek mengembangkan mikroskop lensa tunggal, apa yang mustahil dicerap oleh mata manusia menjadi mungkin. Seseorang akhirnya bisa mengamati ekstensi yang paling kecil sekalipun semisal sel darah merah, bakteri, atau protozoa. Teknologi mikroskop—yang mulanya dikembangkan pertama kali oleh Zacharias Jansen—mentransformasikan pengalaman manusia kejangkauan lebih detail dan luas mengenai dunia sekitarnya.
Dulu, para ilmuwan dipusingkan dengan fakta-fakta astronomi yang terbelah menjadi dua: apakah bumi mengelilingi matahari (heliosentris) atau malah matahari yang mengelilingi bumi (geosentris). Copernicus percaya pada temuan Hipacrus, bahwa teori heliosentrislah yang benar. Sementara Ptolemeus percaya pada teori geosentris.
Lantas, bagaimana fakta-fakta astronomi ini menemukan titik temu kepastiannya? Pengembangan teleskop oleh Galileo akhirnya menyudahi kebingungan itu. Dengan bantuan teleskop, Galileo mampu mengamati gunung-gunung dan ceruk kawah di Bulan, dan fakta-fakta astronomik lainnya, yang sebelumnya tak bisa dijangkau oleh pencerapan indrawi manusia. Kemudian, pengamatan-pengamatan Galileo itu memberi kepastian kebenaran terhadap heliosentris—meskipun kemudian Galileo dihadapkan pada petaka, karena gerejawan waktu itu lebih menyepakati asumsi Ptolemeus.
Dari penjelasan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pengetahuan yang dibangun secara teknologis bisa lebih jelas dan pasti ketimbang mengandalkan fungsi alamiah pencerapan. Ilmu pengetahuan akhirnya turut berkembang melalui temuan-temuan persepsi manusia yang dimediasi oleh teknologi. Pun demikian dengan teknologi informasi. Ia hadir semakin memudahkan manusia untuk mengetahui kehidupan di belahan bumi yang lain tanpa harus bersusah payah ke sana.
Informasi-informasi yang tumpah ruah dalam dunia cyberspace semakin memudahkan menggali pengetahuan baru. Orang-orang bahkan sanggup melakukan komunikasi jarak jauh dengan bantuan Whatsapp. Tapi di sisi lain, kepalsuan, kebohongan, juga bisa berseliweran di tengah-tengah limpahan informasi dalam dunia cyberspace yang setiap hari kita masuki dan beraktivitas di dalamnya melalui perantara teknologi informasi.
Latar belakang inilah yang membuat saya tertarik mengkaji problem pengetahuan dalam hubungan manusia dan teknologi di era cyberspace. Di sisi lain, teknologi dapat menjadi perpanjangan indera manusia dalam mempersepsi realitas yang sulit dijangkau oleh indera alamiah. Namun, di hadapan teknologi informasi, manusia justru rentan keliru dalam mempersepsi realitas, dan bisa salah dalam meyakini kebenaran sebuah informasi.
Problem epistemologi (pengetahuan) tersebut pada akhirnya akan membawa kajian ini ke sebuah penelusuran lebih jauh tentang problem ontologis (realitas) cyberspace. Dunia yang setiap hari kita jelajahi melalui mediasi teknologi informasi. Dunia di mana antara kebenaran dan kepalsuan, fakta dan fiksi, realitas dan fantasi saling silang sengkarut, yang membuat kita menjauh dari kebenaran justru di tengah kelimpahan informasi yang tumpah ruah di ruang virtual.
Hubungan Manusia, Teknologi, dan Dunia Kehidupan
Manusia hidup dalam dunia kehidupan. Dalam pengertian fenomenologi dunia kehidupan adalah dunia yang dihayati oleh manusia. Husserl menyebut dunia manusia sebagai Lebenswelt, dunia yang diciptakan (dimaknakan) dan dihidupi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.[1] Namun, sangat susah membayangkan manusia hidup tanpa teknologi. Manusia mengatasi setiap kesulitan-kesulitan dalam dunia kehidupannya dengan menggunakan teknologi. Manusia dengan mudah menggali tanah dengan cangkul, seorang yang rabun dapat melihat dunia dengan jelas melalui mediasi kacamata, manusia dapat saling berkomunikasi jarak jauh melalui sambungan telepon. Dari teknologi paling sederhana hingga yang paling canggih memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia.
Tak hanya memudahkan aktivitas keseharian manusia. Teknologi bahkan memiliki peranan penting dalam mentrasformasikan pengalaman manusia terhadap dunianya. Artinya, dunia kehidupan dimaknai dan dihayati melalui perantara artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan bisa semakin luas berkat bantuan teknologi. Dari sini, teknologi bisa membantu manusia untuk mengetahui realitas secara lebih baik, dan sekaligus membantu manusia dalam menemukan pengetahuan baru tentang realitas yang sebelumnya tak pernah diketahui.
Don Ihde, pesohor fenomenologi instrumentasi mengatakan, dalam kenyataannya dunia kehidupan tanpa teknologi adalah sebuah ilusi. Sehari-hari manusia hidup dengan menggunakan teknologi. Maka, teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunia kehidupan. Manusia yang bertubuh mempersepsi dunia melalui teknologi.[2]
Itu artinya, teknologi membantu manusia menyingkap kebenaran. Maka dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Heidegger, teknologi tak hanya harus dipahami sebagai sesuatu yang instrumental dan antropologis. Jika teknologi dipandang sebagai sarana, maka teknologi dipandang sebagai sekadar instrumen. Jika teknologi dipandang sebagai aktivitas manusia, maka teknologi hanya dipandang dalam penafsiran antropologis. Meskipun hal tersebut tidak salah, namun bagi Heidegger pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Teknologi mesti juga dilihat dalam arti ontologis, yakni suatu cara kebenaran mengungkapkan dirinya atau latar belakang di mana benda-benda atau peristiwa memunculkan diri dengan cara tertentu.[3]
Jika kebenaran terungkap melalui teknologi, maka kata Heidegger, teknologi merupakan suatu cara penyingkapan (lichtung)[4]. Saat penyingkapan ini terjadi, tersingkap pula aletheia, atau kebenaran. Dan pandangan tersebut sesuai dengan akar kata dari teknologi, yakni techne yang berasal dari bahasa Yunani. Menurut Heidegger, techne mempunyai arti bukan hanya keahlian menukang dengan tangan, namun juga seni pikiran dan seni halus. Techne berhubungan dengan episteme dalam Yunani Kuno yang berarti pengetahuan. Techne melibatkan pengetahuan praktis, episteme melibatkan pengetahuan teoritis. Pengetahuan ini membawa suatu penyingkapan. Artinya techne adalah suatu cara penyingkapan terhadap apa yang belum berada di depan kita. Misalnya bagaimana seorang tukang membuat piala dan melalui keahliannya itu piala menyingkapkan diri atau di munculkan ke hadapan.[5]
Sebagaimana contoh yang saya sebutkan sebelumnya, seseorang yang memiliki mata rabun dapat melihat dunia dengan lebih jelas melalui mediasi kacamata. Di sini, kacamata sebagai teknologi adalah suatu cara penyingkapan dunia kehidupan manusia. Pengalaman manusia terhadap dunia kehidupannya dimediasi oleh teknologi. Manusia mempersepsi dunianya melalui teknologi. Meski manusia dapat mempersepsi dunianya tanpa teknologi. Namun dengan bantuan teknologi, persepsi manusia terhadap dunianya ikut berubah. Tentu akan berbeda persepsi kita terhadap bulan tanpa bantuan teleskop dan dengan menggunakan teleskop. Detail-detail bulan yang kasar bisa kita amati, padahal sebelumnya kita mempersepsi bulan sebagai benda langit bulat yang halus ketika dilihat dengan pencerapan mata semata.
Menurut Don Ihde, dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua indera. Sementara makropersepsi adalah persepsi manusia yang diperoleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada seperti cara berpikir, pemikiran yang sudah ada dalam diri manusia. Di samping dua persepsi itu, ada dimensi ketiga yang disebut Ihde sebagai dimensi teknologis di mana manusia memahami dunia kehidupan melalui instrumen.[6]
Saking pentingnya pengaruh teknologi terhadap manusia, pengalaman manusia pun sangat ditentukan dengan penggunaan instrumen. Meski demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Ihde, hal yang tak boleh diabaikan juga adalah dalam penggunaan teknologi terdapat struktur magnifikasi dan sekaligus reduksi. Magnifikasi berarti pembesaran objek yang diteliti secara visual. Jadi terdapat peningkatan dan penajaman pada ciri tertentu dari realitas saat dipersepsi melalui teknologi. Namun demikian, struktur reduksi di sisi lain juga akan terjadi.[7]
Contohnya adalah penggunaan teleskop untuk meninjau bulan. Dengan menggunakan teleskop seseorang bisa melihat detail permukaan bulan yang tak akan kelihatan jika hanya mengandalkan penglihatan semata. Inilah yang disebut magnifikasi. Tapi pada saat yang sama terjadi reduksi yakni aspek lain dari bulan menjadi tidak kelihatan. Bulan tidak lagi dilihat sebagai benda bulat yang bertengger di tempat tertentu di luasnya langit malam.
Namun terlepas dari itu, pengalaman manusia menjadi berubah dengan bantuan teknologi. Bahkan hubungan manusia-teknologi menghasilkan berbagai macam pengalaman terhadap dunia kehidupan. Dalam fenomenologi instrumentasi yang dikembangkan Ihde, ada empat variasi hubungan manusia-teknologi yang membuat pengalaman manusia terhadap dunianya menjadi beragam. Namun saya hanya akan membahas dua hubungan saja, yakni hubungan kebertubuhan dan hermeneutis karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang saya angkat pada tulisan ini.
Pertama, hubungan kebertubuhan. Di dalam hubungan kebertubuhan, alat digunakan sebagai perpanjangan tangan dari tubuh manusia. Alat juga menjadi sebagian dari tubuh manusia dalam relasinya dengan dunia sekitarnya.[8] Kita kembali menggunakan contoh kacamata. Seseorang yang memiliki mata rabun dapat melihat dunia dengan lebih jelas melalui mediasi kacamata. Tubuh dan instrumen bersifat relasional. Realitas dapat dilihat, didengar, dirasakan melalui instrumen.[9] Hubungan kebertubuhan dapat digambarkan sebagai berikut.
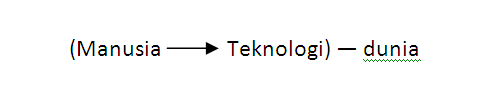
Kedua, hubungan hermeneutis. Menurut Budi Hartanto, hubungan hermeneutis menjelaskan relasi antara manusia dengan instrumen sebagai yang terpisah dari tubuh. Dalam hal ini realitas yang dipersepsikan berada dalam instrumen itu sendiri. Konsekuensinya, dalam relasi hermeneutis diperlukan pembacaan.[10] Di sini, posisi teknologi seperti teks yang perlu diterjemahkan agar dapat dipahami. Sehingga yang menjadi objek persepsi adalah sesuatu yang dibaca dan menjadi teks di dalam teknologi.
Contoh yang paling baik adalah termometer yang dipasangkan di dinding luar rumah. Termometer tersebut menunjukkan suhu 40oC. Angka tersebut jika ditafsirkan akan menghasilkan pemahaman jika cuaca di luar rumah sedang panas. Penafsiran terhadap realitas bisa benar sejauh instrumen menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Namun, jika objek pada instrumen tersebut bukan keadaan sebenarnya maka realitas pun sulit untuk diketahui. Hubungan hermeneutis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
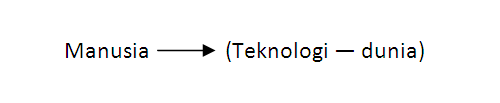
Sekarang mari fokus pada teknologi informasi, instrumen yang menjadi fokus perhatian dalam tulisan ini. Jika merujuk pada dua varian hubungan manusia-teknologi perspektif Ihde, maka hubungan manusia dengan teknologi informasi bisa sebagai hubungan kebertubuhan, dan juga hubungan hermeneutis. Smartphone misalnya, adalah alat yang multifungsi. Alat tersebut bisa digunakan untuk menelepon, mengirimkan pesan singkat berbentuk teks, menonton video, mengambil gambar baik berupa foto, bermain game, dan melakukan interaksi sosial dengan menggunakan aplikasi media sosial.
Saat digunakan sebagai sarana telepon, maka antara pengguna dengan smartphone-nya memiliki hubungan kemenubuhan. Karena smartphone menjadi perpanjangan indera penggunanya untuk mendengar suara orang lain yang berkedudukan di tempat yang jauh dengan bantuan instrumen.
Di sisi lain, hubungan manusia dengan smartphone bisa sebagai hubungan hermeneutis. Smartphone menghadirkan objek persepsi dalam bentuk virtual seperti teks, video, maupun foto. Manusia perlu menafsirkan informasi dalam bentuk realitas virtual tersebut agar dapat memahami realitas yang tampil di balik layar smartphone. Realitas virtual inilah yang saat ini kerap dibilangkan sebagai cyberspace.
Karena segenap kejadian-kejadian dunia, informasi terkait situasi terkini, dicari melalui dunia maya, bahkan interaksi sosial antar manusia dilakukan melalui dunia maya, maka era saat ini kerap pula dibilangkan sebagai era cyberspace. Dunia dipersepsi dalam bentunya yang virtual, sejumlah aktivitas sosial, ekonomi, bahkan politik manusia pun dilakukan dengan berselancar di dunia maya. Namun apakah manusia dapat memahami dunianya dengan baik jika dunia yang dipersepsi direpresentasikan dalam bentuk cyberspace? Pertanyaan tersebut menjadi permasalahan yang menjadi tujuan utama dalam tulisan ini, dan akan dibahas dalam bagian selanjutnya.
Cyberspace : Ketika Realitas Menjadi Citra
Jika kacamata atau teropong masih menghubungkan manusia dengan dunia kehidupannya, maka lain halnya dengan teknologi informasi. Ia menghubungkan manusia dengan dunia cyberspace yang artifisial dan imajiner. Objek-objek dalam cyberspace berbeda dengan objek-objek yang kita persepsikan secara langsung maupun dengan instrumen dalam dunia harian kita. Objek dalam cyberspace berwujud maya.
Lebih jelas Yasraf Amir Piliang mengatakan, cyberspace bukan mimpi, tetapi ia bukan yang nyata dalam arti dunia harian, disebabkan ia dibangun oleh ruang-ruang artifisialitas teknologis. Bila dikaitkan dengan arus kesadaran dalam durasi kehidupan manusia, cyberspace bukanlah dunia ketaksadaran atau bahwah sadar, melainkan dunia kesadaran, yang di dalamnya seseorang mengalami sebuah objek di luar dirinya lewat mekanisme penginderaan (gestalt). Akan tetapi, pengalaman yang dialami seseorang di dalam cyberspace berbeda dengan pengalaman di dunia nyata, disebabkan perbedaan objek yang ditangkap oleh pengalaman. Di dalam cyberspace, setiap orang lewat kesadarannya menangkap objek-objek namun kesemuanya bukanlah objek-objek nyata, melainkan objek-objek maya yang terbentuk lewat bit-bit komputer.[11]
Perbedaan objek inilah yang menjadikan dunia cyberspace menjadi persoalan serius, khususnya menyangkut kualitas pengetahuan manusia yang dihasilkan melalui pemaknaan terhadap dunia maya yang dimediasi oleh teknologi informasi. Karena objek-objek dalam cyberspace bukanlah objek-objek fisik yang dialami secara nyata. Realitas itu sendiri diubah menjadi objek citra yang bersifat artifisial, fantasi, virtual, dan maya. Meski objek-objek dari cyberspace adalah gambaran dari dunia nyata (ada juga objek-objek dalam cyberspace yang tak memiliki referensi di alam nyata dan murni fantasi) namun objek fisik dunia nyata tersebut telah ditransformasikan menjadi wujud citra.
Untuk itulah, sebagaimana yang dikatakan Yasraf, cyberspace adalah sebuah migrasi besar-besaran dari dunia fisik ke dalam dunia citraan, sehingga di dalamnya segala yang ada dalam dunia realitas (bahkan yang belum ada sama sekali) menemukan eksistensinya dalam wujud realitas artifisial. [12] Migrasi tersebut bukan dalam arti bahwa realitas citra dalam cyberspace adalah representasi dari realitas. Karena representasi masih memungkinkan adanya persamaan. Namun, realitas citra dalam cyberspace sudah terputus dari realitas, tak memiliki referensi yang jelas.
Ia adalah tiruan dari realitas, namun bersifat artifisial karena objek-objek dalam cyberspace hanyalah realitas buatan melalui pemograman kode yang rumit dari teknik komputasi. Maka dari itu, fakta dan fiksi, realitas dan citra, kepalsuan dan kebenaran sudah saling silang sengkarut dalam dunia cyberspace. Karena objek-objek citra dapat dimanipulasi, diduplikasi, digandakan, didekonstruksi, ruang dapat direkonstruksi sesuka hati. Gagasan tersebut akan membawa kita pada istilah simulasi yang digagas oleh Baudrillard.
Simulasi bagi Baudrillard tidak lagi berkaitan dengan duplikasi “ada” atau substansi dari sesuatu yang diduplikasi, melainkan penciptaan melalui model-model sesuatu yang nyata tanpa asal-usul atau realitas. Referensi dari duplikasi bukan lagi sekadar realitas, melainkan apa yang tidak nyata. Karena fantasi dapat disimulasi menjadi seolah-olah nyata, maka perbedaan antara realitas dan fantasi sudah tidak ada.[13]
Baudrillard mengemukakan ada beberapa tahap dalam perkembangan simulasi menjadi realitas. Tahap pertama, simulasi masih merupakan refleksi dari sebuah realitas yang diacunya. Kedua, simulasi menutup dan membelokkan realitas sehingga realitas tak lagi hadir apa adanya. Ketiga, simulasi menutup kehadiran realitas yang diacunya. Tahap keempat simulasi meniadakan seluruh bentuk relasi dengan realitas apa pun. Tahap empat ini simulasi menjadi simulacrum murni. Tahap lanjut simulasi adalah kehadiran hiperealitas yakni ketika citra menjadi realitas.[14]
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dunia cyberspace adalah dunia objek-objek citra hipereal yang lahir melalui proses simulasi. Bagi baudrrillard, simulasi adalah proses atau strategi intelektual, sedangkan hiperealitas adalah efek, keadaan, atau pengalaman kebendaan dan atau ruang yang dihasilkan dari proses tersebut.[15]
Terjebak dalam Hiperealitas
Ketika realitas yang dihadapi dalam cyberspace adalah objek citra yang manipulatif dan artifisial, maka pemahaman kita terhadap objek tersebut sangat berpotensi keliru. Sebab objek yang kita persepsi di dalam layar smartphone dan komputer adalah hiperealitas di mana fakta dan fiksi, keaslian dan kepalsuan, realitas dan fantasi, benar dan salah sudah bercampur baur. Hubungan manusia dan teknologi informasi di era cyberspace akhirnya menghasilkan suatu problem serius mengenai pengetahuan terhadap realitas yang dihadirkan melalui instrumen canggih tersebut.
Jika kita sedang memainkan smartphone, segala foto-foto yang berhamburan di media sosial, video viral yang dibagikan sampai jutaan orang, atau pun identitas- identitas pengguna Facebook adalah sebuah objek citra yang tak lagi jelas kebenaran dan kesalahannya, apakah itu fakta atau fiksi, nyata atau fantasi. Perempuan berkulit sawo matang dalam kehidupan nyata bisa menjadi putih bagai aktor Korea dalam unggahan fotonya di Facebook karena sudah dimanipulasi sedemikian rupa melalui aplikasi editing foto. Anda bahkan bisa berteman dengan seseorang di Facebook yang mengaku perempuan namun identitas sebenarnya adalah laki-laki.
Pun, seseorang bisa membuat story di Instagram yang menampilkan rekaman dirinya berada di sebuah restoran mewah dengan makanan super mahal. Dengan sentuhan filter Instagram, wajahnya bisa terlihat bersih terawat khas anak orang kaya. Tujuan dari itu semua adalah hendak menciptakan citra kelas atas dan teman-temannya terkesima dengan kesuksesannya, padahal ia hanya pemuda kelas menengah yang lagi beruntung sedang ditraktir oleh teman kayanya.
Itu adalah beberapa contoh dari objek-objek citra yang kerap kita temukan saat berhubungan dengan dunia maya melalui perantara teknologi informasi. Namun kita kerap terjebak dalam kesalahan persepsi, keliru dalam menafsirkan objek citra, karena realitas yang kita hadapi sungguh berbeda dengan dunia fisik keseharian. Di dunia maya, kita akan dihadapkan pada kenyataan di mana segala hal yang bertentangan, saling silang sengkarut: melumernya batas-batas fakta-fiski, baik-buruk, benar-salah.
Maka bisa jadi konstruksi pengetahuan kita yang dibentuk dunia maya kita anggap benar padahal sebenarnya salah, atau malah sebaliknya. Akan sangat mudah jika Anda ingin mengubah persepsi orang-orang terhadap Buya Syafi’i. Anda tinggal meng-upload foto Buya Syafi’i yang diedit secara profesional dengan menyelipkan perempuan di sampingnya, maka kondisi pemahaman orang-orang turut berubah. Bahkan penjahat bisa kita anggap bermoral, tergantung kode-kode pencitraan yang menjadi representasi fiktif yang Anda lekatkan padanya dalam objek citra.
Telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa hubungan antara manusia dan teknologi informasi adalah hubungan hermeneutis. Dalam hal ini realitas yang dipersepsikan berada dalam instrumen. Di sini, posisi teknologi seperti teks yang perlu diterjemahkan agar dapat dipahami. Namun, jika teks pada instrumen tersebut tidak menunjukkan keadaan sebenarnya maka realitas pun tak bisa diketahui. Realitas yang tampil dalam layar smartphone kadang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Maka untuk itulah kekeliruhan bisa terjadi saat menafsirkan objek citra yang tumpah ruah dalam dunia cyberspace.
Don Ihde memberi istilah lain untuk realitas yang mewujud secara fragmentasi lewat teknologi dengan nama plurikulturalitas. Plurikulturalitas menurut Ihde ada ketika realitas hadir secara teknologis dalam sebuah medium sehingga terciptalah imej kultur global. Lewat artefak teknologi, seperti televisi, kamera foto, sinema, komputer, imej diproduksi dan direproduksi.[16] Maka dalam konteks plurikulturalitas, cyberspace adalah ruang di mana dunia kehidupan mewujud sebagai citra dalam artefak teknologi. Dunia kehidupan cyberspace dalam pengertian plurikulturalitas menghadirkan realitas kebudayaan yang beragam.
Hal tersebut menjadi jelas ketika kita berselancar di dunia maya, dan didapati banyak objek-objek citra yang datang silih berganti dengan menampilkan keanekaragaman budaya global. Bagaimana tidak, puluhan juta orang di seluruh dunia saat ini terkoneksi satu sama lain melalui jaringan internet. Komunitas virtual pun tercipta tanpa dihalangi oleh sekat-sekat batas seperti batas geografis, nasionalitas, agama, kebudayaan, dan negara-bangsa. Keberagaman budaya yang tumpah ruah dalam dunia cyberspace pun tak terhindarkan lagi.
Plurikulturalitas menghargai dan menikmati keberanekaragaman. Dalam keberagaman ini, setiap budaya dihormati dan tidak ada satu budaya yang dianggap lebih unggul. Konsep budaya atau pusat budaya sudah tidak ada. Dalam arti ini, plurikulturalitas mirip dengan pascamodernisme di mana perbedaan dan budaya-budaya kecil diangkat.[17]
Meski demikian, meleburnya batas-batas dan berimigrasinya dunia kehidupan ke dalam realitas citra menjadikan objek-objek persepsi dalam teknologi informasi semakin sulit dipahami. Sebab, batas-batas antara yang nyata dan yang fiksi, antara realitas dan citra, antara kebenaran dan kepalsuan telah hilang dan objek-objek hadir sebagai realitas manipulatif dan artifisial sehingga keasliannya telah hilang.
Realitas pun sangat berpotensi untuk tereduksi, yakni aspek lain dari realitas menjadi tidak kelihatan. Misanya gambar foto yang menceritakan peristiwa pembunuhan yang viral di media sosial. Di dalam foto tersebut terdapat seseorang yang memegang sebilah pisau dan seorang lagi yang tengah terluka akibat tikaman pisau. Jika melihat kejadian tersebut dalam bentuk foto, seseorang bisa mengira bahwa sang pemegang pisau tersebut adalah pelakunya, meski kejadian sebenarnya adalah sang pemegang pisau tersebut datang setelah kejadian tersebut dan hendak menolong korban. Hanya saja ia tertangkap kamera saat sedang memegang barang bukti berupa pisau.
Problem ontologis dan epistemologis yang kompleks dalam cyberspace tak hanya menghasilkan permasalahan reduksi tersebut. Namun juga sifat artifisial dan manipulatif dari objek citra menghasilkan banyak kekacauan. Karena menjadikan pemahaman seseorang terhadap realitas yang tampil di dunia maya tidak utuh. Kita bisa saja terkesima dengan melihat indahnya panorama alam dalam sebuah video, namun fenomena alam tersebut sudah tak tampil sebagaimana adanya, karena videografer telah memanipulasi realitas tersebut dengan teknik editing melalui aplikasi tertentu. Sehingga panorama alam yang sebenarnya tak seindah dalam video tersebut bisa menjadi lebih indah, artistik, lebih terang, dan lebih nyata.
Bahkan di dunia maya, seorang Jokowi tak lagi bisa dibedakan antara seorang presiden dan artis, politisi dan aktor. Saat Jokowi meninjau perbatasan Kalimantan di akhir tahun 2019 lalu, terlihat dalam sebuah video di dunia maya, ia dan pengawalnya menelusuri Trans Kalimantan dengan menunggangi motor custom. Warganet pun berdebat apakah Jokowi hanya sekadar pencitraan, atau memang sebagai presiden gaul yang sangat peduli dengan warga pedalaman. Perbedaan persepsi tersebut sangat bisa terjadi, mengingat video tersebut telah mengaburkan batas-batas antara tugas kepresidenan, enterteiment, kesungguhan, kerja, liburan, realitas apa adanya, atau sekadar pencitraan. Di dunia cyberspace, apa yang kita saksikan bukan lagi sebagai realitas yang sejati.
Mencari Jalan Keluar
Lantas bagaimana jalan untuk keluar dari jebakan hiperealitas dalam cyberspace? Jalan yang paling memungkinkan adalah bersikap kritis pada setiap objek-objek citra. Sekali lagi bahwa hubungan manusia-teknologi informasi adalah hubungan hermeneutis. Objek-objek citra yang kita hadapi di dalam teknologi informasi perlu ditafsirkan serupa teks, agar mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap realitas yang dicitrakan dalam ruang virtual. Sifat hermeneutis dalam hubungan manusia-teknologi informasi member peluang pada manusia untuk memaksimalkan potensi berpikirnya agar lebih kritis dalam membaca setiap objek-obek citra.
Sebagaimana yang dikatakan Francis Lim, citra selalu berhubungan dengan konsep “dengan melihat berarti percaya”. Konsep ini dikaitkan dengan pengalaman tubuh akan dunia kehidupan melaui teknologi citra. Di sini, diperlukan suatu sikap kritis terhadap realisme instrumental, yaitu sikap untuk selalu kritis dan mempertanyakan apa yang dilihat melalui teknologi citra. Citra yang ditampilkan melalui teknologi harus dipersoalkan secara kritis sebelum menerima bulat-bulat realitas oleh teknologi tersebut karena di dalamnya terkandung penyingkapan dan penyembunyian.[18]
Penyingkapan dan penyembunyian yang terkandung objek-objek citra karena objek citra sendiri adalah hiperealitas yang mengaburkan batas-batas realitas, fantasi, kebenaran, kepalsuan, nyata dan ilusi. Sehingga objek citra mengandung aspek magnifikasi dan reduksi sekaligus. Pada aspek magnifikasi, terjadi penginkatan dan penajaman pada realitas sehingga realitas dapat ditelaah dengan lebih jelas. Pada aspek magnifikasi ini, realitas dapat tersingkap.
Tapi pada sisi lain, realitas tidak tampil secara keseluruhan sehingga terjadi reduksi. Realitas hanya potongan-potongan fragmen yang bahkan telah dimanipulasi sehingga menghilangkan keasliannya. Maka pada posisi ini, kebenaran akan tetap tersembunyi karena terhalangi oleh sifat manipulatif dan reduksi dari realitas tersebut. Sehingga sikap kritis adalah jalan yang paling memadai untuk keluar dari jebakan hiperealitas dunia maya.
Saya mendefinisikan sikap kritis sebagai sikap yang tak mudah percaya akan suatu hal sebelum diperiksa kebenarannya melalui verifikasi dan analisa yang mendalam. Maka kita sebaiknya terbiasa bersikap spektis terhadap citra-citra yang tumpah ruah dalam cyberspace. Kemudian membedah realitas tersebut sampai ke akar-akarnya, sampai kebenaran yang tersembunyi bisa menyingkapkan dirinya. Usaha tersebut semata-mata sebagai cara agar tetap waras saat berselancar di dunia maya.[]
Catatan Kaki:
[1] Zainal Abidin, Analisis Eksistensial untuk Psikologi dan Pskiatri (Bandung: Refika, 2002) hlm 9
[2] Francis Lim, Filsafat Teknologi Don Ihde Tentang Dunia, Manusia, dan Alat (Yogyakarta: Kanisius, 2008) hlm 80
[3] Ibid hlm 43-46
[4] Arti kata lichtung adalah pembukaan atau pembersihan hutan. Namun Heidegger lebih mengaitkannya dengan kata licht yaitu cahaya, maka berarti penerangan. Lihat, Budi Hardiman, Heidegger dan Mistik keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit (Jakarta: KPG, 2008) Cetakan ke II, hlm 67
[5] Francis Lim, op.cit, hlm 50
[6] Ibid, hlm 82-83
[7] Ibid, hlm 85
[8] Ibid, hlm 102
[9]Budi Hartanto, Dunia Pasca-Manusia: Menjelajahi Tema-tema Kontemporer Filsafat Teknologi (Depok: Kepik, 2013) hlm 8
[10] Ibid hlm 9
[11] Yasraf Amir Piliang, Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial, Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012, hlm 146 (diakses di : https://media.neliti.com/media/publications/41503-none-dcf5b5fa)
[12] Ibid, hlm 149
[13] Yasraf Amir Piliang, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna (Bandung: Jalasutra, 2003) hlm 32
[14] Hikmat Budiman, Lubang Hitam Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2002) hlm 82
[15] Yasraf Amir Piliang, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna op.cit, hlm 135
[16] Budi hartanto, op.cit, hlm 12
[17] Franis Lim, op.cit, hlm 142
[18] Ibid, hlm 149
Ilustrasi: https://humanrights.gov.au/our-work/rights-and-freedoms/publications/human-rights-and-technology-discussion-paper-2019
