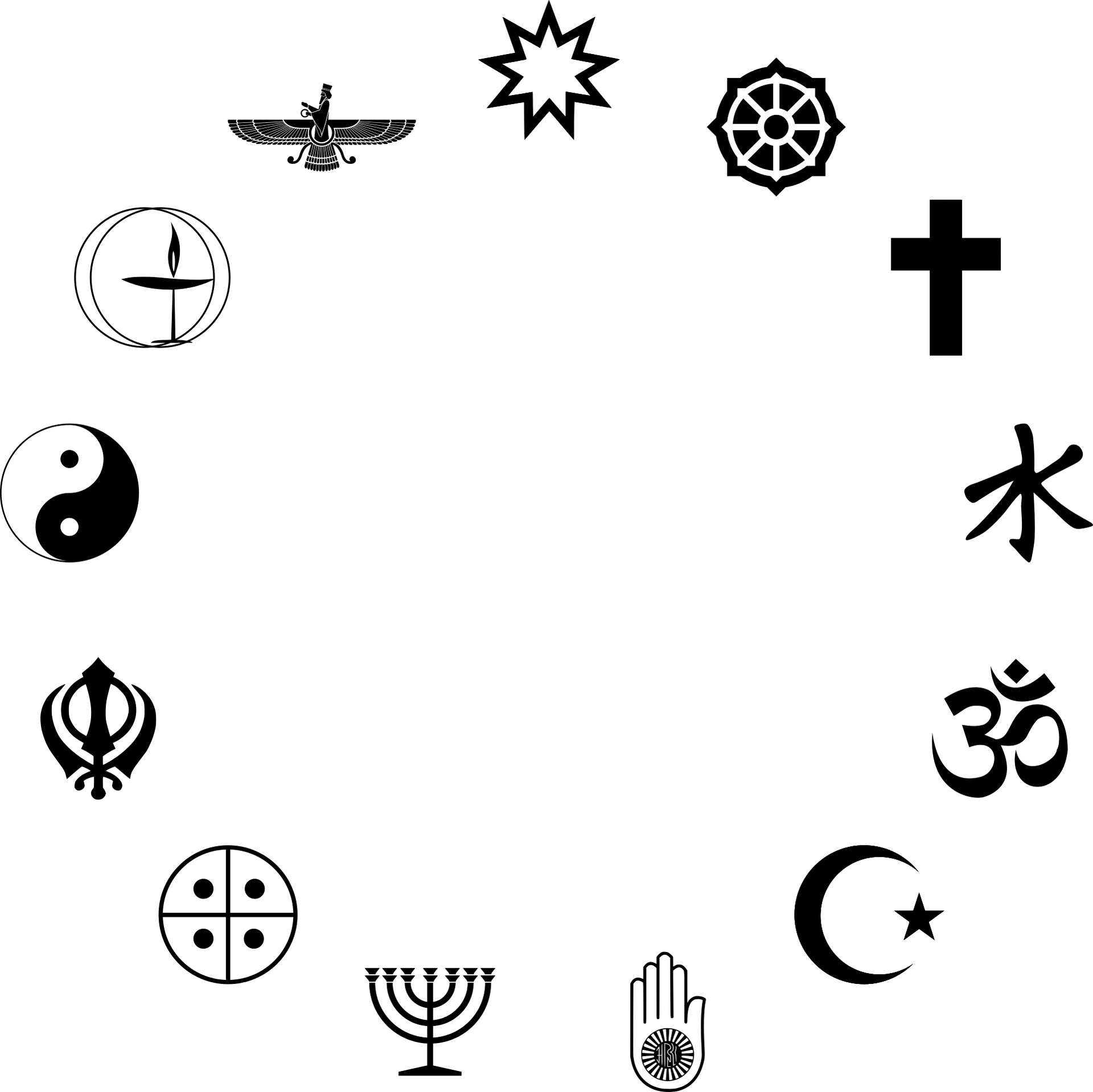Judul tulisan ini, saya terinspirasi dari Maksim Daeng Litere “Paripurnakanlah Cinta Agama Menjadi Agama Cinta”. Status singkat, prinsipil dan inspiratif sejenis itu, rutin ditulis oleh Sulhan Yusuf (Saya lebih akrab memanggilnya Kak Sul/Sulhan) pada beranda akun facebooknya setiap hari pada pagi hari.
Ahmad Faizin Karimi dalam buku Membaca Korona (2020), saya menangkap pesannya bahwa di antara makhluk hidup, manusialah yang paling terkoneksi antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ini membentuk jejaring sosial kehidupan. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Faizin Karimi dari Stanley Milgram, menyimpulkan sebagian besar manusia di dunia ini terhubung dengan rata –rata “enam derajat keterpisahan”. Contoh: Presiden Amerika itu, temannya teman dari teman dari teman dari teman dari teman saya.
Masih dalam tulisan pencerahan Ahmad, saya memahaminya bahwa “enam derajat keterpisahan” itu dalam koneksi secara fisik dan konvensional. Berbeda dengan koneksi secara virtual, itu lebih dekat lagi jaraknya, bahkan jika saya hubungkan dengan tesis “Dunia yang Dilipat” Yasraf Amir Piliang bisa disebut “tanpa batas”. Ini membentuk jejaring maha besar. Christakis & Flower menyebutnya “hyper-connected”.
Dalam koneksi dan relasi kehidupan manusia ini, baik secara fisik (konvensional) maupun virtual tidak terlepas dari sebuah problematika yang merupakan paradoks dari the ultimate goal manusia itu sendiri: “kebahagiaan”. Meskipun lazimnya, selain berupaya mencapai kebahagiaan manusia juga berupaya mencapai kesuksesan. Tetapi ingat sukses belum pasti bahagia.
Sebagaimana bisa kita baca dalam buku Tasawuf Modern karya Prof. Dr. Hamka (Buya Hamka) yang terbit pertama kali 1939, berbagai pendapat tentang bahagia mulai dari pemikir Islam klasik, termasuk perspektif dari para filsuf tanpa kecuali Aristoteles, defenisi dan pemahamannya berbeda–beda. Meskipun saya bukan seorang mufasir (ahli tafsir) tetapi saya menarik sebuah konklusi (kesimpulan) bahwa hakikat hidup itu adalah “bahagia”.
Kesimpulan ini saya tarik dari premis yang bersumber dari firman Allah yaitu pada QS. Az – Zariyat/51: 56 “Manusia diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah” dan QS. Ar- Ra’du/13: 28 “Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram (bahagia)”. “premis-premis” (firman) dan konklusi ini saya anggap benar, karena saya (pemeluk agama Islam) mengimani Al-Qur’an.
Segala dinamika yang terjadi dalam jejaring sosial kehidupan tersebut, pada dasarnya diharapkan bermuara pada “kebahagiaan”. Bahagia disimpulkan berasal dari dalam diri, bukan dari luar sehingga dinamika yang saya maksudkan di sini bukanlah dalam perspektif materiil atau capaian–capaian materi. Melainkan dinamika yang bersifat intelektual, emosional, dan spiritual.
Ada banyak fenomena dalam realitas empirik yang bagi saya sangat paradoks dengan kebahagiaan atau menjadi pemantik ketidakbahagiaan. Dan aktor–aktornya secara psikologis itu tidak bahagia. Mungkin saja ada yang mengklaim bahwa ini adalah “kebahagiaan”, apalagi jika fenomena yang dimaksud menurutnya memiliki basis teologis (ada dalil pembenarannya). Namun kita perlu berhati–hati mendefenisikan dan merasakannya karena bisa jadi kesenangan yang menyamar/menjelma menjadi kebahagiaan.
Fenomena–fenoma yang saya maksudkan antara lain: Hoax terus diproduksi dan direproduksi. Yang lebih parah daripada hoax itu ada radikalisme, ekstrimisme, terorisme, intoleransi, korupsi, amoral, antipati, takfiri, truth claim, resisten, chaos, making fun, kriminal anti kritik, anti dialog. Saya berani menyimpulkan bahwa aktor dari semua ini, sesungguhnya itu kurang bahkan tidak bahagia.
Apalagi jika saya mengorelasikan dengan QS. Az- Zariyat/51:56 di atas, fenomena yang saya sebutkan bukan dalam konteks menyembah kepada Allah. Saya mencoba memahami frasa “menyembah kepada Allah” bukan cuma dalam konteks “beribadah”, apalagi jika ibadah yang dimaksud adalah ibadah vertikal. Tetapi saya memahami frasa “menyembah kepada Allah” itu adalah bagaimana agar segala aktivitas kehidupan manusia dalam dimensi “rida Allah”. Kata kuncinya “rida Allah”.
Meretas semua problematika dan fenomena tersebut, maka penting menghadirkan “cinta” dan “agama” pada diri manusia dan dalam jejaring sosial kehidupan manusia. Cinta dan agama merupakan modal psikologis dan teologis yang sangat urgen dan vital bagi manusia dalam mengarungi kehidupannya. Pemahaman terhadap “cinta” dan “agama” itu tidak tunggal bahkan dari keduanya berpotensi ⸻ khususnya agama ⸻ memiliki wajah ambigu (meminjam istilah Asratillah).
“Cinta” dan “agama” yang sebagian anasirnya sesungguhnya telah built-in pada diri manusia bersama kelahirannya, memiliki potensi yang bukan hanya menjadi pemantik pencapaian the ultimate goal manusia tetapi justru sebaliknya. Menjadi basis lahirnya fenomena yang saya sebutkan di atas dan paradoks dengan kebahagiaan tersebut.
Membaca tiga tulisan (sub judul) yang memiliki relevansi dengan “agama” dalam buku Hasrat Kebenaran karya Asratillah (2014), agama bukan hanya membantu manusia membaca makna yang tiada batas, menjelaskan posisi manusia di tengah tengah kosmos, mengingatkan keterhubungan antara manusia yang profan dengan seuatu yang transenden dan memicu tekad manusia. Ternyata agama juga memicu benih yang tak membawa kebahagiaan: menciptakan musuh, truth claim, takfiri, terorisme, radikalisme ,hasrat kekuasaan dan lain lain.
Hal ini terjadi karena kita hanya menilai sebagaimana pandangan Asratilah “…mengira agama adalah sesuatu eksisten yang independen di alam metafisik sana”. Secara substansial bisa jawaban “iya”. Tetapi Asratillah juga mengingatkan, bahwa kita jangan lupa, agama yang kita anut, kita bela dan yang kita hujat adalah agama yang termanusiakan. Ini relevan dengan pembacaan Haidar Bagir dalam buku karyanya Islam Tuhan Islam Manusia (2017).
Untuk tujuan mulia dan utama manusia: “kebahagiaan”, penting kiranya memformulasikan antara modal psikologis (cinta) dan modal teologis (agama) dalam jejaring sosial kehidupan manusia. Formulasi yang dimaksud, adalah bagaimana kita mencintai agama. Ini juga bisa berarti bagaimana menghadirikan cinta yang dilandasi oleh agama (nilai–nilai dan ajaran agama). Setelah itu, bagaimana mengimplementasikan agama cinta, agama yang memancar dengan penuh cinta.
Inilah yang saya maksudkan “Dari Cinta Agama Menjadi Agama Cinta”, untuk diurai lebih jauh agar mampu meretas fenomena kehidupan yang paradoks dengan kebahagiaan dan dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup. Saya menyadari bahwa persoalan “cinta”, “agama”, “cinta agama” dan “agama cinta” merupakan tema yang sangat luas dan dalam. Jadi tulisan saya ini, betapapun panjang narasi yang saya goreskan dengan argumentasi dan referensi yang jelas tetapi ini hanya setetes atau percikan perspektif dalam pemahaman saya yang masih terbatas. Setetes air pengetahuan dari samudera ilmu pengetahuan.
Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, tulisan ini sudah satu pekan saya rumuskan (rangkai), beberapa kali saya rombak/bongkar total (edit) karena tema ini bukan cuma menunjukkan hal paradoks antara pemahaman saya yang masih terbatas dibandingkan tema yang amat luas dan dalam. Tetapi tema ini pula sangat sensitif, fundamen bahkan merupakan persoalan yang paling purba, lebih tua dari sains. Sebagaimana dikutip oleh Asratillah dari sosiolog positivistic, August Comte “Fase agama adalah fase yang lebih primitif dari fase metafisika apalagi fase positif”. Komaruddin Hidayat menyimpulkan “agama punya seribu nyawa”.
“Dari Cinta Agama Menjadi Agama Cinta”, ditilik dari Habitus Pierre Bourdieu, “Dari Cinta Agama” itu saya menilai sebagai proses internalisasi eksterior. Menyerap substansi cinta yang relevan dengan nilai–nilai agama yang otentik dan cinta itu sendiri menjadi pemantik agar dalam proses internalisasi (menyerap) nilai dan ajaran agama secara baik dan benar. Untuk memudahkan pemahaman secara baik dan benar, singkatnya relevan sebagaimana Asratillah memahami agama yang termanusiakan dan dalam perspektif Haidar Bagir memahami Islam Tuhan dan Islam Manusia.
Sedangkan “Agama Cinta” itu merupakan proses eksternalisasi interior. Bagaimana menghadirkan agama dalam realitas kehidupan dengan penuh cinta sebagai hasil pemahaman agama yang baik dan benar. Mengedepankan spirit cinta sebagai refleksi agama yang otentik. Sederhananya agama cinta itu relevan dengan Tasawuf Modern-nya Buya Hamka (2015) ⸻ terbitan pertama 1939, Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan-nya Haidar Bagir (2012), The Garden of Truth-nya Seyyed Hossein Nasr (2007), Teologi Al-Ma’un dan Etos Welas Asih-nya KHA. Dahlan (1912-), dan Spiritualitas Ihsan-nya Ary Ginanjar Agustian. Tanpa kecuali relevan dengan konsep Islam Berkemajuan dan Kosmopolitanisme-nya dan Neo-Sufisme-nya Muhammadiyah.
Meskipun cinta oleh sebagian pujangga menilainya sesuatu yang misteri namun ada banyak defenisi tentang cinta. Cinta memiliki kekuatan yang dahsyat untuk melakukan transforrmasi baik kehidupan personal maupun sosial. Cinta dalam perspektif tertentu ada yang mengarah pada hal–hal yang negatif dan destruktif, maka di sinilah signifikansi cinta harus dilandasi dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Agar cinta yang lahir adalah merefleksikan cinta yang ideal. Cinta ideal merefleksikan cinta kepada Allah dan cinta-Nya Allah kepada hamba-Nya.
Bersambung pada bagian kedua…
Ilustrasi: Serat.Id