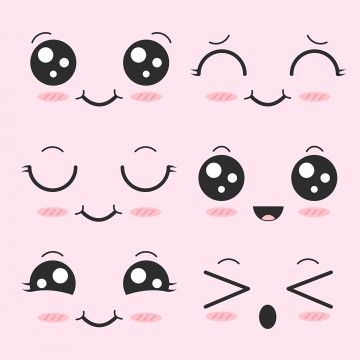Ternyata, menjadi dewasa itu tak cukup menyenangkan. Bukan, bukan tak cukup, tapi memang tidak menyenangkan sama sekali. Sewaktu kecil, kita sering berimajinasi menjadi orang dewasa itu pastilah seru: punya banyak duit, tidak harus tidur siang, mandi semau-maunya, dan bisa ke sana kemari tanpa dimarahi ibu. Semua imaji itu akhirnya porak-poranda ketika masuk ke gerbang kedewasaan. Ternyata menjadi dewasa itu sungguh menyedihkan. Orang dewasa punya segudang problema kehidupan. Mereka hanya pandai berpura-pura baik-baik saja. Dan sialnya, dengan kematangan otak yang dimiliki, justru menjebaknya dalam labirin masalahnya sendiri. Anak kecil itu mudah melupakan masalah, orang dewasa sebaliknya.
Semasa kecil, ketika punya masalah dengan teman—bahkan berkelahi sekalipun. Besoknya kita sudah bermain bersama lagi, tak ada dendam sama sekali, seolah masa lalu tak pernah ada. Sebuah kemewahan yang tidak dimiliki orang dewasa.
Sebaliknya, di usia kita yang sekarang, masalah sekecil apa pun justru sering dibesar-besarkan, makin merenggut stok kebahagiaan kita yang sebenarnya tidak banyak-banyak amat. Kita bertengkar soal sepele, soal remeh temeh, dan takhayul. Hanya karena berbeda pendapat, saling hujat. Hanya karena politik, rusak susu sebelaga. Atau bagi pasangan muda mudi, hanya karena pesan dibalas lama, pikiran langsung menjadi hama. Setelahnya bertengkarlah sudah, masalah lebih besar pasti datang: dongkol seharian. Sepertinya, selain melupakan, orang dewasa juga susah saling memahami satu sama lain.
Makanya, aku ingin jadi anak kecil saja. Masa di mana kebahagiaan begitu mudah merasuk dalam dada. Waktu di mana masa lalu tak datang mengganggu dan masa depan tak pernah menunggu. Anak kecil menikmati semua-muanya saat itu juga. Itulah mengapa mereka membenci tidur siang. Tak ada kenikmatan dalam tidur, sebab kehidupan nyata, selalu lebih indah daripada mimpi-mimpi mereka.
Sedang bagi orang dewasa, tidur seringkali menjadi satu-satunya pelarian dari peliknya hidup. Tidur begitu nikmat bagi, sebab di sanalah mereka bisa melupakan semuanya. Ah, sebenarnya bukan kehidupan yang pelik, kita hanya butuh peluk. Merangkul diri dan mengajaknya berdamai, berhenti memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Hidup memang begini, jadi biasakanlah diri.
Di sekolah, menjadi anak kecil mesti dimasukkan dalam daftar cita-cita. Masa di mana tidak ada sesuatu yang mustahil. Semua anak pasti pernah bercita-cita jadi power ranger, entah merah, hijau, biru, atau hitam. Sekotahnya terasa mungkin, hingga hidup menjadi optimistis dan penuh gairah. Ketika dewasa, kita kemudian menyadari bahwa hidup tak semudah itu. Jam tangan kita hanya menunjukkan waktu, tak bisa membuat kita jadi power ranger yang punya kekuatan adimanusia.
Kita pun menjadi lebih realistis dengan keadaan, sedang sikap demikian justru mengaburkan anugerah khayali yang dialamatkan Tuhan. Padahal, kata seseorang yang bukan peneliti, mengkhayal itu cara otak memberikan jeda pada pikiran untuk beristirahat. Tak percaya? Coba praktikkan! Pikiran akan terasa lebih tenang ketika mengkhayal. Kalau tidak, berarti Anda mengkhayalkan sesuatu yang salah—mungkin masa lalu yang masih jadi benalu. Entahlah.
Di sisi lain, hanya dengan mengkhayallah kita bisa menjadi apa saja dan siapa saja, dan itu gratis. Meski hanya dalam pikiran, walau nisbi dan rapuh. Tapi setidak-tidaknya itu bisa membuat pikiran mengembara dan melupakan sejenak masalah yang membara.
Sayangnya, sikap realistis yang dimiliki orang dewasa mengacaukan segalanya. Antara realistis dan pesimistis kadang sulit dibedakan. Orang selalu bersembunyi di balik kata realistis untuk menutupi rasa pesimisnya. Ya, begitulah, seperti yang saya bilang di awal, kita begitu pandai berpura-pura. Manusia yang kehilangan imajinasi, berarti kehilangan separuh dirinya. Hidup sudah berat di kehidupan nyata, larilah ke dunia imaji yang membebaskan.
Ya, seandainya, menjadi anak kecil adalah sebuah tempat, maka aku ingin mengajak kau ke sana. Laiknya mengunjungi nenek di kampung halaman dengan kereta, seperti bunyi syair Aan Mansyur dalam Cinta yang Marah.
“Suatu hari kelak, sebelum salah satu di antara aku dan kau tersangkut maut, pada hari ulang tahun kau, ketika tidak ada pekerjaan kantor yang melarang kau cuti, aku akan mengajak kau menjadi tua renta, kemudian mengajak kau kembali menjadi anak-anak.”
….
“besoknya, aku akan membuat sepasang layang-layang. aku akan mengajak kau ke padang lapang, jika aku sudah menemukan padang, aku dan kau akan memanjat ke atap gedung yang menyerupai tanah lapang di mana seseorang entah siapa sering memarkir pesawat. di sana, aku dan kau akan bermain layang-layang hingga puas. mungkin aku dan kau sepasang tubuh dewasa yang tidak lagi memiliki jiwa anak-anak. siapa tahu layang-layang menerbangkan aku dan kau kembali ke masa kecil, ketika senja masih bening, ketika pohon-pohon masih hijau, ketika cinta belum terlalu rumit untuk dipahami.”
***
Apakah orang dewasa memang ditakdirkan tidak bahagia? Hmm, Sepertinya memang begitu.
Ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang di dunia ini mengalami kurva kebahagiaan berbentuk U, ini berdasar pada riset yang dilakukan terhadap ribuan orang di 132 negara, oleh seorang profesor bernama David Blanchflowers dari Darmouth, sebagaimana dilansir Inc.com yang juga dikutip kumparan.
Dalam penelitian itu dijelaskan, ketika seseorang mulai menginjak usia 18 tahun, level kebahagiaan mulai berkurang, hingga mencapai usia 60 tahunan. Puncaknya, ketika usia tiba di 47,2 tahun di negara maju, dan 48,2 tahun di negara berkembang. Kemudian setelah mencapai usia 60 tahun, level kebahagiaan bisa beranjak naik kembali. Itulah alasan kurvanya dibilang berbentuk U.
Mengapa hal tersebut terjadi? Pertama soal ekspektasi, di usia 20-an, kita meyakini bahwa mimpi dan keinginan akan mudah tercapai. Ternyata tak segampang itu, karena tidak semua orang dilahirkan seperti Rafathar. Ada banyak rintangan dalam perjalanan, dan tak semuanya bisa dilangkahi dengan mudah, bahkan ada yang memang tak bisa dilangkahi sama sekali. Kebahagiaan pun makin menipis. Setipis dompet anak muda.
Kedua, soal mengomparasi diri dengan orang lain. Masih meminjam pendakuan Blanchflower, orang di usia 20, 30, hingga 40-an sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita merasa orang lain sudah jadi “manusia” karena pencapaian-pencapaiannya dalam hal tertentu, dan kita merasa masih begini-begini saja. Merasa jalan di tempat, bahkan mundur. Perasaan rendah diri itu pun muncul, dan rasa bahagia sisa sebakul.
Ya, sebenarnya tak ada yang salah dengan membandingkan, tapi tahu dirilah. Jika tak pas, alih-alih menambah motivasi, justru orang sering terjebak pada tekanan batin. Jadi, cara terbaiknya adalah membandingkan diri yang sekarang dengan diri yang kemarin. Itu baru adil dan setara. Kalau kita menjadi lebih baik, itu artinya ada progres. Jika tidak, dan bahkan lebih buruk, berarti Anda memang tidak layak bahagia, Bung. Jadi jangan salahkan Tuhan.
Lalu, bagaimana agar hidup bahagia? Sukses? Bagaimana kita mendefenisikan kesuksesan? Oke, punya banyak uang, sebut saja begitu—paling tidak itulah ukuran mayoritas masyarakat kita. Saya ingin mengajukan pendakuan Martin Seligman, seorang pelopor Psikologi Positif, yang meneliti hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan di berbagai negara, sebagaimana dipaparkan oleh Arvan Pradiansyah dalam bukunya The 7 Laws of Happiness.
Bagi Seligman, daya beli dan kepuasan hidup rata-rata di suatu negara berbanding lurus. Tapi ketika GNP (Gross National Product) melebihi 8000 dolar per jiwa, korelasi ini sirna dan penambahan kekayaan tidak menaikkan level kepuasan hidup. Jadi, jika ada yang bilang tidak butuh uang untuk bahagia, tampaknya agak sulit jika menilik temuan Seligman. Sederhananya, kita tidak bisa berbahagia dengan perut lapar, kan?
Menariknya, di Jepang, walau masyarakatnya punya daya beli mencapai skor 87, tapi tingkat kepuasan hidupnya hanya 6,53 (dari skala 1—10). Sedang India yang skor daya belinya hanya 5, tetapi tingkat kepuasan hidupnya mancapai 6,70. Ini menunjukkan bahwa uang tidaklah bisa membeli kebahagiaan. Meski sulit juga bahagia tanpa uang.
Nah, bagi Seligman, di negara-negara miskin, tempat kemiskinan bisa mengancam nyawa, menjadi kaya berarti lebih bahagia. Tapi ketika garis kemiskinan sudah terlampaui, tingkat ekonomi tidak lagi memainkan peran dalam menentukan kebahagiaan manusia. Ya, artinya selama hidup berkecukupan—meski tidak kaya—kita bisa lebih bahagia dari pada konglemerat atau artis yang begelimang harta benda.
Saya jadi ingat dengan tokoh Oh Il Nam, ayah dari Seong Gi-Hun, dalam film Squid Game, katanya, “Ada persamaan antara orang yang tidak memiliki uang dan yang memiliki terlalu banyak uang, hidup tak menyenangkan bagi mereka. Jika kau punya terlalu banyak uang, apa pun yang kau beli akan membosankan pada akhirnya.”
Arvan Pradiansyah kemudian menarik benang merahnya. Bahwa memang ada faktor-faktor yang memengaruhi kebahagiaan, seperti kekayaan, kesehatan yang baik, dan persahabatan dengan orang lain. Namun, pada akhirnya penentu dari segalanya adalah pikiran.
“Apabila kita memiliki pikiran yang tenang dan damai, faktor-faktor pendukung kebahagiaan tersebut bisa berpengaruh. Saya yakin orang sehat yang memiliki pikiran damai akan lebih bahagia dibandingkan dengan orang miskin yang memiliki pikiran damai.” Ujar Arvan.
Akhirnya, kita tiba pada sebuah konklusi sederhana, bahwa kunci dari semuanya tersimpan dalam laci bernama pikiran. Jika, hidup orang dewasa tidak bahagia, itu karena kita terlalu banyak memikirkan hal-hal negatif yang sebenarnya sudah terjadi dan belum terjadi. Kita hanya perlu menarik nafas dalam-dalam dan bersikap lebih tenang, sembari berucap semua kan baik-baik saja. Seperti pesan Dalai Lama, “Makin tinggi tingkat ketenangan pikiran kita, makin besar pula kedamaian yang kita rasakan, makin besar kemampuan kita menikmati hidup yang bahagia dan menyenangkan.”
Tunggu apalagi? Wahai anak muda, berbahagialah kini, sebab kita tak bisa kembali masa kecil, dan masa tua belum tentu tiba. Sayang sekali hidup ini, Tuhan pasti sedih jika manusia tidak menikmatinya.
Berbahagialah, seolah-olah hari ini adalah yang terakhir.
Ilustrasi: pinterest.com